Alhamdulilah bisa ikut merayakan lebaran 2018, atau 1439 H. Tanpa berita kemacetan yang berarti, meski tetap saja ada. Macet akan sulit dihindari, di tengah banyaknya pengguna kendaraan pribadi.
Juga tanpa berita kenaikan harga pangan yang ekstrem. Meski pada lebaran begini, konsumsi masyarakat naik. Pesta makan, juga rumah-rumah yang menyuguhkan kue-kue, yang bahan bakunya bermacam-macam, tepung dan gula terutama.
Akan tetapi nilai tukar rupiah terhadap dollar masih sulit beringsut dari angka yang mengkhawatirkan. Rasanya sulit untuk bergeser, apalagi ketika Donald Trump sedang menerapkan kebijakan konservatifnya, mirip ideologi partainya, yang dikenal dengan America first
Uang yang ada, termasuk investasi didahulukan untuk kepentingan Amerika. Nampak pada kampanyenya dahulu, yang seolah anti imigran, juga anti muslim. Akan dibangun tembok di perbatasan, terutama dengan Mexico.
Belakangan cara kampanye Trump diikuti oleh kelompok tertentu di Indonesia, yang terus mendengungkan bahayanya pekerja asing, hutang negara, juga pribumi harus berdaulat.
Semua itu memang penting, dan harus diupayakan. Tetapi beda lagi jika dipolitisir demi dapat suara rakyat. Amerika adalah negara dengan hutang terbesar, namun lembaga penghutangnya, bisa mereka kendalikan. Itulah uniknya.
***
Sampai pertengahan Juni, dari berbagai lembaga survey kredibel, elektabilitas Jokowi masih diatas 50%. Menyusul Prabowo, dan calon-calon lain dibawah 10%. Sebenarnya ada banyak kandidat.
Perlu kerja lebih keras, bahkan kalau perlu dengan cara yang tak biasa, untuk menurunkan elektabilitas Jokowi. Perlu menggali lagi hal-hal yang sekiranya bisa menjatuhkan, entah apa, biarlah oposisi "bekerja".
Namun pemerintah, juga tidak tinggal diam. Melalui berbagai instrument kebijakan dan kuasanya, seperti bagi-bagi sertifikat tanah. Diam, tapi menghanyutkan.
Padahal waktu terus bergulir, bulan depan sampai maksimal Agustus, kandidat pilpres 2019 mungkin sudah harus diumumkan. Hanya Jokowi yang secara kalkulasi bisa maju. Mayoritas partai berkumpul mendukungnya.
Prabowo sepertinya masih bimbang. Apakah berduet dengan PAN lagi, atau PKS. Keduanya adalah pilihan sulit. Dari suara parlemen, PAN unggul. Tetapi dari kesetian, PKS paling bisa diharapkan.
PKS pun terus "bekerja" dengan tagar 2019 ganti presiden. Banyak yang ikut gerakan ini, tetapi mungkin tak banyak tahu kalau penggagasnya adalah kader PKS, Mardani Ali Sera. Mardani adalah satu dari sembilan capres/cawapres yang ditawarkan PKS.
Prabowo sepertinya sedang menunggu dan melihat, mana sosok-sosok yang bekerja paling keras, untuk kemudian dipilih sebagai cawapres. Jika melihat sejauh ini, Mardani adalah sosok yang paling sukses menggempur presiden. Sayangnya, Mardani tidak begitu menjual untuk dijadikan cawapres.
Trauma dengan pilpres 2014 silam, yang mana Prabowo bisa menang diatas kertas, apalagi mayoritas parpol mendukungnya. Hanya saja pasangannya, Hatta Rasjasa, elektabilitasnya sangat rendah. Andai kala itu yang jadi pasangannya adalah Mahfud MD, mungkin beda lagi.
Prabowo sudah bertarung sejak 2004. Sudah habis-habisan. Dana sudah banyak yang terkuras. Maka wajar jika penuh pertimbangan. Ia tentu tidak mau mengukir sejarah sebagai capres yang selalu gagal.
Karenanya sempat muncul nama-nama non parpol, seperti Gatot Nurmantyo dan TGB yang lagi moncer-moncernya. Mendengar itu, parpol koalisi, terutama PKS dan mungkin juga PAN, agak gusar.
Pak Amien Rais tiba-tiba menyatakan diri siap Nyapres lagi. Seperti petir di siang bolong, padahal PAN sedang gencar-gencarnya memprofilkan Dzulkifli Hasan.
Belum lagi ketika Habib Rizieq Shihab (HRS) juga menyatakan siap nyapres. Makin banyak alternatif, makin menunjukkan tidak solidnya koalisi Umat atau apalah namanya.
Nampak bahwa kekuasaan, secara alamiah sangat menggiurkan untuk diperebutkan.
Karenanya Jokowi nampak santai, sekalipun ia diserang dari berbagai arah. Serangan bertubi-tubi. Serangan untuk kebijakan-kebijakan yang diambil, sampai serangan personal.
Jokowi masih di atas angin, lawan politiknya sedang dirundung kebimbangan yang akut.
Tetapi sebentar dulu, beberapa tokoh kembali mengajukan judificial review UU Pemilu, yang mana syarat nyapres adalah 0%. Jika MK meloloskan, maka semua partai bisa mengajukan capres dan cawapresnya sendiri, akan terbuka peluang bagi banyak tokoh.
Ini juga bisa berdampak pada parpol yang mendukung Jokowi, yang mungkin juga akan sedikit goyah. Tergoda untuk mengusung sendiri, meski dengan peluang menang yang kecil.
Betapapun hebatnya tokoh, butuh beberapa bulan, atau beberapa tahun, untuk menaikkan elektabilitas. Inilah kenapa petahana selalu kuat, apalagi Jokowi yang selalu show up di media : blusukan, aktif di sosmed, terbuka pada wartawan, dan tentunya, memiliki banyak penghujat. []
Blitar, 17 Juni 2018
Ahmad Fahrizal Aziz


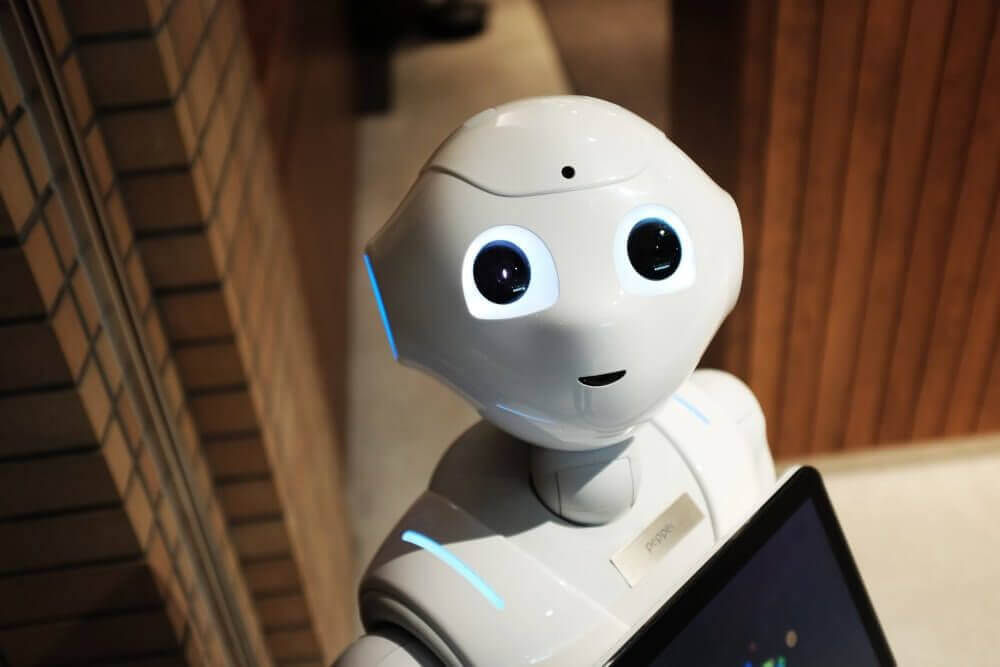








Follow Us
Were this world an endless plain, and by sailing eastward we could for ever reach new distances